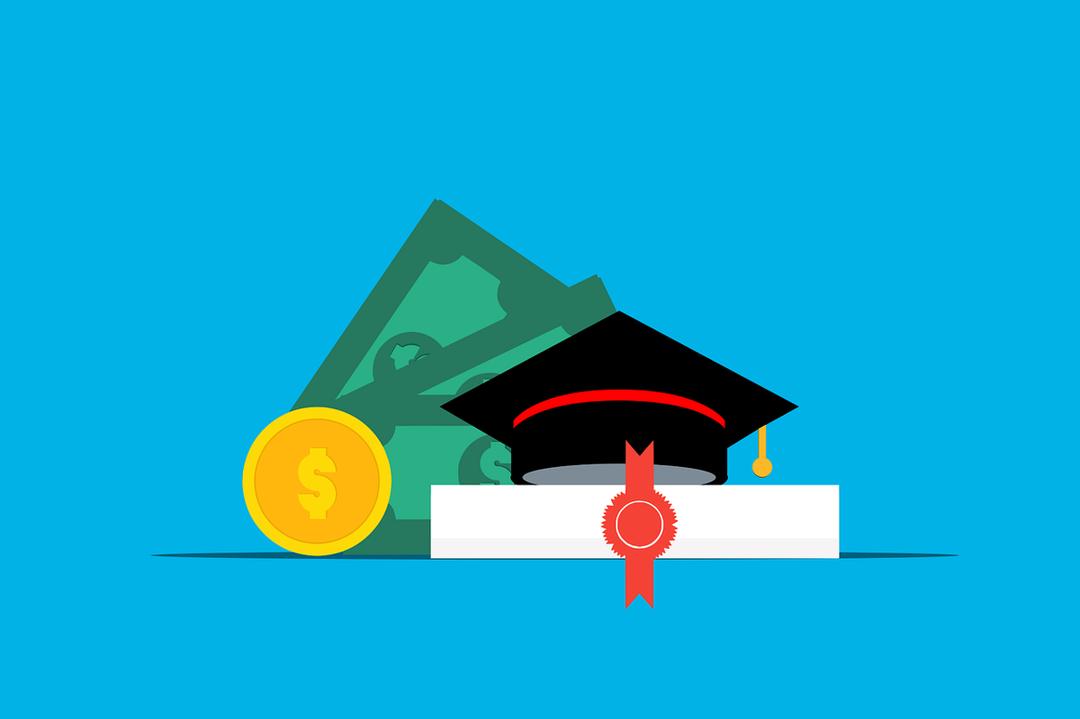“Mereka bukan borjuis bukan pula proletar, tapi Prekariat atau kelas pekerja baru yang bebas tapi tak berdaya”
Balada Gen Z, Freelance dan Perangkap Eksploitasi

Generasi Z (Gen Z) memilih freelance karena fleksibilitas waktu dan tempat kerja.
Freelancer mengalami tantangan seperti manajemen waktu, ketidakpastian pekerjaan, dan kurangnya transparansi dalam kontrak kerja.
Perlindungan hukum untuk pekerja lepas sangat dibutuhkan karena banyak perusahaan yang memanfaatkan freelancer tanpa memberikan jaminan sosial dan kesehatan.
Surabaya, IDN Times - Lea (21) adalah seorang mahasiswi yang juga pekerja freelance sebagai kru di salah satu wedding organizer di Jawa Timur. Tujuan Lea, menambah uang saku dan tabungan. Ia juga ingin menambah lebih banyak teman dan lebih mengenal dunia kerja yang sebenarnya.
"Untuk waktu dulu mikirnya weekend bisa berkegiatan freelance, tapi ternyata cukup challenging karena dulu awal-awal masih join Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus waktu weekend. Kalau ekspektasi ke beban kerja gak terlalu sih karena menganggap jadi crew itu seru walaupun agak ngeri-ngeri sedap,” kata Lea.
Lea mengaku, salah satu tantangan menjadi freelancer adalah di manajemen waktu. Karena selain bekerja freelance Lea harus menjalankan kesibukannya sebagai mahasiswa magang. Ia mengaku sudah tiga bulan ini ia sering absen untuk berkontribusi di pra acara dan acara pernikahan wedding organizer-nya.
“Ada rasa takut tiba-tiba dikeluarin juga, karena kan sistemnya freelance bukan pekerjaan tetap. (freelance-ku) kalau gak ngerjain kamu ditegur, tapi kalau gak aktif lagi kamu langsung dikeluarin,” ungkap Lea.
Tidak sampai di situ, Lea pun memaparkan bahwa ia pernah mengalami kebingungan di awal-awal masa training bekerja karena tidak adanya transparansi yang detail dalam kontrak kerjanya.
“Pernah aku ditugaskan di acara nikah di salah satu posisi yang bisa dibilang ringan, tapi jaraknya jauh banget dari lokasi kos. Di kontrak perjanjian gak ada tugas itu, begitu juga nominalnya. Karena jaraknya jauh banget dari kos dan tugasnya gak ditulis di kontrak, alhasil aku kaget kok kayak gak setimpal (gaji dan tugasnya). Sebenarnya harus detail kan kontrak, tapi itu gak gitu,” tutupnya.
Cerita freelancer juga datang dari Rahmi Dwi Alyani. Gen Z asal Lampung ini memilih jalur freelance bukan sekadar mengikuti tren, melainkan keputusan yang sangat personal. Ia merasa fleksibilitas waktu membantunya tetap bisa mengurus rumah sekaligus menemani orang tua.
“Selain itu, aku bisa hemat biaya transportasi, baju, dan makeup,” kata Rahmi.
Rahmi menjalani freelance dengan mengelola kelas digital miliknya pribadi. Dari sisi waktu, ia merasa jauh lebih bebas.
Ia bisa mengatur jadwal sesuai kebutuhan peserta dan ritme kerjanya sendiri. Meski begitu, tekanan tetap ada, bukan dari klien atau beban kerja, melainkan dari ekspektasi pribadi.
“Aku punya target atau KPI sendiri, tapi kadang belum tercapai. Jadi penghasilannya masih unstable. Tekanannya lebih ke diri sendiri, sih,” ujar Rahmi.
Meski freelance masih ia jadikan side hustle, Rahmi percaya karier ini punya prospek besar di masa depan. Dalam bayangannya, 5–10 tahun mendatang pekerjaan freelance akan semakin besar, global, sekaligus diakui secara formal.
“Lebih besar, karena perusahaan bakal makin banyak pakai tenaga freelance. Lebih global, karena platform digital bikin kita bisa bersaing di pasar internasional. Lebih terlindungi, karena mungkin nanti ada regulasi standar kontrak dan jaminan sosial. Lebih hybrid, karena orang bisa gabungin freelance, kontrak pendek, plus bisnis sampingan,” ujarnya.
Namun, ia juga realistis. Tidak semua orang cocok menjadikan freelance sebagai jalur utama. “Kalau gak adaptif sama zaman, gak inovatif, gak punya skill relevan, apalagi gak bisa bahasa internasional, ya sulit. Ditambah lagi freelancer gak punya pensiun, jadi harus pandai atur keuangan,” tutupnya.
Kerja freelance banyak diminati para Generasi Z (Gen Z) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka memilih kerja freelance karena fleksibilitas waktu dan tempat kerja. Salah seorang pekerja Gen Z di Kota Mataram, NTB, Siti Suhaera (25) mengatakan bekerja freelance karena sistem kerjanya yang fleksibel.
"Sebagian Gen Z begitu, gak suka masuk pagi pulang sore. Aku pilih pekerjaan yang fleksibel. Yang kerjanya bisa dari mana saja tanpa ke kantor," kata Suhaera kepada IDN Times di Mataram, Minggu (21/9/2025).
"Gen Z itu rata-rata tidak satu pekerjaan. Banyak side job-nya walaupun sudah kerja tetap. Ada kerjaan sampingannya. Kalau aku content writer itu bebas. Tulis artikel juga bisa, gak nulis juga bisa. Gak ada tuntutan buat artikel segini sehari," tuturnya.
Dia mengungkapkan dalam sebulan bisa mendapatkan penghasilan dari kerja freelance sekitar Rp1,9 juta. "Kalau mau banyak dapat penghasilan perbanyak artikel saja," tambahnya.
Cerita lain datang dari Dicki Nur Sidik, anak muda asal Wates, Kulon Progo yang kini berkarier di Jakarta sebagai fotografer lepas. Ia mengaku cukup menikmati pekerjaannya karena menjadi freelancer membuatnya lebih bisa merasakan hidup sekaligus berkembang.
"Aku sangat menikmati sebagai freelance," ujar Dicki.
Dicki mulai menekuni dunia kerja sejak 2017. Ia mengaku pekerjaan sebagai karyawan tetap sudah tidak lagi potensial baginya. Menurutnya, menjadi freelancer sama halnya dengan membangun bisnis bersama diri sendiri, yang justru dianggap lebih menjanjikan. Apalagi jika pekerjaan itu sudah mampu menciptakan alat sendiri sekaligus market sendiri.
Tak hanya soal finansial, Dicki juga melihat rezekinya bisa datang lewat berbagai pengalaman baru. "Aku jadi bisa tahu karakter orang lebih luas, tahu venue atau lokasi foto yang bagus seperti hotel atau restoran," katanya.
Hal-hal semacam itu, lanjut Dicki, jarang ia temukan ketika bekerja sebagai karyawan kantoran. Ia bahkan membandingkan gaji pekerja tetap yang dalam sebulan mungkin berkisar Rp7-8 juta, sementara dirinya sebagai freelancer bisa meraup pendapatan sekitar Rp15 juta.
Satu hal yang paling disyukuri Dicki sebagai fotografer lepas adalah waktu kerja yang lebih fleksibel. Sudah berkeluarga, ia merasa beruntung tidak harus rutin nine to five ke kantor setiap hari sehingga bisa memiliki waktu berkualitas bersama anak.
Namun, fleksibilitas ini juga bagai dua sisi mata pisau. Jadwal yang tak menentu sering kali menyulitkan, terutama saat menerima pekerjaan dari vendor yang membuatnya bekerja lebih lama dari perjanjian. Meski berstatus pekerja lepas, hampir setiap hari tetap ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
"Aku kan sering ambil job graduation, di kampus-kampus, jadi weekday juga jalan," ujarnya. Waktu luangnya pun kerap dihabiskan untuk menyunting foto dan mengurus file, selain melaksanakan pekerjaan rumah. Sebagai seorang ayah, ia menyadari tugasnya tidak hanya mencari nafkah, tapi juga ikut berperan dalam urusan domestik.
Beralih pada kisah Sekar gen z asal Bali lulusan 2024 lalu. Dia telah melamar ke empat perusahaan media dengan penempatan di luar Bali. Namun, hingga saat ini belum ada panggilan.
Ada tiga pekerjaan yang dia coba selain bidang jurnalistik, yaitu penulis naskah drama, petugas layanan konsumen, dan penulis naskah di agensi kreatif. Ia melihat semua lowongan itu dari aplikasi penyedia kerja. Dari ketiga lowongan, ada dua yang berhasil lolos. Yaitu sebagai petugas layanan konsumen, dan penulis naskah di agensi kreatif.
Alasan Sekar memilih freelancer karena pekerjaan formal kurang mendukung kesehatan mental. Sekar pernah melakoni pekerjaan sebagai petugas layanan konsumen atau customer service officer di tempat les musik kawasan Kota Denpasar. Selama seminggu, Sekar hanya dapat libur sehari dengan gaji pada masa percobaan sebesar Rp2 juta. Jika berhasil melewati masa probasi, Sekar mendapat gaji sekitar Rp3 juta. Angka ini di bawah upah minimum kota (UMK) Denpasar. Tahun 2025, Denpasar menetapkan UMK sebesar Rp3.298.116.
Sementara, hak pekerja seperti asuransi kesehatan dan tunjangan hari raya (THR) akan Sekar dapatkan setelah setahun bekerja. Sekar harus tiba di kantor pukul 07.40 Wita, dan tidak boleh melewatkan daftar hadir menggunakan sidik jari. Jika melewati pukul 07.50 Wita, Sekar harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp20 ribu. Selama masa probasi, Sekar kerap lembur dan baru pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 Wita, dengan uang lembur Rp10 ribu per jam. Sedangkan jam normal pulang kerja di kantor tersebut pukul 18.00 Wita.
Keterampilan kerja sebagai petugas layanan konsumen yang belum Ia miliki sepenuhnya, membuat Sekar kerap bertanya kepada rekan kerjanya yang sudah lebih dulu bekerja. Namun, bukannya menjadi mentor, rekan kerja Sekar kerap sinis.
Sekar hanya bertahan 23 hari di tempat kerja formal itu. Beban psikologis dominan menjadi tekanan. Dia pun rela untuk sementara memilih menjadi penulis magang yang memang bagian dari keahlian liniernya sebagai sarjana komunikasi. Gaji tak seberapa tapi kesehatan mental terjaga.
Curhatan para freelancer gen z itu merupakan bagian kecil dari jutaan orang di Indonesia yang memilih untuk jadi freelancer. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja bebas mencapai 12. 576. 594 orang di bulan Agustus 2023. Di bulan yang sama di tahun berikutnya, jumlah itu meningkat menjadi 13. 023. 561 orang.
Data ini juga dikuatkan dengan hasil survei dari Indonesia Millennial and Gen Z Report 2026 oleh IDN Research Institute. Mayoritas responden atau sebanyak 84 persen gen z dan milenial menyetujui bahwa fenomena freelance menjadi strategi utama bagi mayoritas generasi muda untuk dapat menuangkan kreativitas, meningkatkan pendapatan, serta mencoba jalur karier baru.
Melalui survei ini, IDN menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei dilakukan pada Februari sampai April 2025 dengan studi metode campuran yang melibatkan 1.500 responden, dibagi rata antara Milenial dan Gen Z.
Survei ini menjangkau responden di 12 kota besar di Indonesia, antara lain Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.
Pun juga seperti cerita para gen z dari beberapa daerah yang diwawancarai IDN Times, mereka ingin menghadirkan perspektif baru terkait karier profesional dan pekerjaan. Mereka tidak lagi sekadar memandang pekerjaan sebagai cara untuk bertahan hidup, melainkan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan nilai personal.
Perangkap eksploitasi mengintai buruh freelance
Namun, kebebasan yang dinikmati freelancer di Indonesia sekarang ini masih jauh dari perlindungan sebagai hak tenaga kerja. Mereka belum mendapatkan payung hukum.
Mengutip dari Buku Pedoman Kerja Kontrak Freelancer SINDIKASI tahun 2019 dari laman sindikasi.org, Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuat regulasi untuk pekerjaan harian lepas (freelance) yang mengatur aspek perjanjian kerja freelance antara di pemberi kerja dengan pekerja. Regulasi tersebut berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 mengenai ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Keputusan Menteri tersebut lebih rinci pelaksanaan dari ketentuan PKWT yang diatur dalam Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Akan tetapi, berdasarkan temuan SINDIKASI, freelancer belum diidentifikasi secara jelas dalam perundangan dan ketenagakerjaan sehingga pekerjaannya tidak tercakup dalam perlindungan. Belum ada regulasi dan hukum yang secara tepat mengatur dan melindungi freelancer. SINDIKASI juga memaparkan bahwa berbagai kerentanan yang dialami oleh pekerja freelance menegaskan fleksibilitas kerja yang menguntungkan mereka hanya mitos yang didengungkan dalam narasi pekerja masa depan dalam revolusi industri 4.0. Kondisi freelancer yang rentan merupakan bukti tidak adanya perlindungan akibat fleksibilitas kerja memperdalam masalah ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu mengakui bahwa ada tren ge z semakin banyak memilih kerja freelance karena waktunya fleksibel, bisa dikerjakan dari mana saja, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta digitalisasi saat ini.
Namun, Agus juga menekankan adanya tantangan besar, yaitu pendapatan yang tidak tetap, keterlambatan pembayaran, hingga ketiadaan jaminan sosial seperti BPJS, pensiun, maupun cuti. Ia menambahkan, belum ada regulasi spesifik mengenai freelance, sehingga perlu adanya inisiatif revisi undang-undang ketenagakerjaan agar bisa mengakomodasi pola kerja baru ini.
Bukan tanpa sadar, para freelancer gen z sangat berharap perlindungan pekerja sangat dibutuhkan. Lea mengaku sudah mencari tahu mengenai risiko apa saja yang akan dihadapi sebelum memasuki dunia kerja freelancer dan sadar bahwa pekerjaan freelance adalah pekerjaan sementara.
Walaupun Lea sudah menjalankan profesi freelance cukup lama dan sudah berada di tahap nyaman, tetapi ia tidak menutup mata terhadap realita yang dihadapi. Mereka telah membaca situasi ekonomi dan kemungkinan lain yang bisa menimpa mereka.
Bahkan, Lea mengaku menyadari adanya perangkap ‘tak terlihat’ berupa jam kerja yang terkadang mengarah ke eksploitasi. Ia melihat sendiri ada perusahaan yang memakai modus seperti memanfaatkan freelancer dari kalangan mahasiswa yang sedang butuh kerja, pengalaman, dan waktu kerja fleksibel.
“Sudah saatnya pemerintah membuatkan payung hukum untuk pekerja lepas,” katanya.
Rahmi juga menyoroti minimnya regulasi yang melindungi freelancer di Indonesia. Dari kontrak kerja, sengketa pembayaran, hingga akses jaminan sosial dan kesehatan, semua masih abu-abu. Akibatnya, banyak freelancer seperti dirinya merasa tidak punya keamanan kerja jangka panjang.
“Pemerintah seharusnya juga lebih jelas soal akses program resmi. Aku aja bingung, kalau mau daftarin kelas digital biar berkembang, ke mana? Minim banget sosialisasi, jadi kelas ini berjalan sendiri tanpa ekosistem pendukung,” keluh Rahmi.
Dicki pun juga pernah mendengar kabar soal eksploitasi terhadap pekerja lepas. Ia sepakat bahwa freelancer membutuhkan payung hukum untuk melindungi mereka dari perusahaan maupun perorangan yang mengambil tenaga dan waktu secara berlebihan.
"Seharusnya ya dapat (perlindungan hukum), seperti pekerja lainnya," ujar Dicki.
Menurutnya, masih banyak vendor besar yang belum memahami regulasi terkait perekrutan pekerja lepas. Baginya, pemerintah perlu membuat aturan yang bisa melindungi sekaligus memberi keadilan bagi setiap masyarakat, apa pun status pekerjaannya. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan antara pemberi kerja dengan pekerja.
Meski begitu, Dicki mengaku jarang menghadapi kesulitan saat bekerja sama, baik dengan vendor maupun perorangan. Soal pembayaran pun aman karena sejak awal kedua belah pihak sudah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing. Ia juga menerapkan sistem down payment (DP) untuk mengikat dirinya sebagai penyedia jasa sekaligus calon klien.
Dicki menyadari pekerjaannya membutuhkan konsistensi jika ingin dijalani sebagai karier jangka panjang. Tak jarang ia sempat bertanya pada diri sendiri, "apa iya sampai tua mau begini terus?" Namun, ia memilih menjalaninya dengan santai, seperti air yang mengalir.
"Aku percaya sih, kalau konsisten dan telaten, akan membuahkan hasil yang baik. Bismillah, ini (pekerjaan freelance) akan baik-baik saja," ujar Dicki.
Mengingat status pekerjaannya tanpa jaminan, Dicki perlahan menyiapkan tabungan untuk masa tua. "Dana pensiun sudah (disiapkan). Disisihkan beberapa persen," akunya.
Selama ini, Dicki lebih banyak bekerja sama dengan vendor, meski sempat terpikir untuk menjajal kerja remote melalui platform tertentu. Kini, ia tetap memilih fokus pada jalur yang sudah dibangunnya sebagai fotografer lepas tanpa melirik cara kerja lain.
Siti Suhaera juga mendorong ada perubahan regulasi oleh pemerintah. Karena mereka juga pekerja yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan.
"Harusnya ada perubahan regulasi biar pekerja freelance juga terlindungi. Karena kan kita sama-sama pekerja juga. Kalau gak mau dikasih perlindungan akomodir semua masyarakat bisa bekerja tetap. Kasih lapangan kerja sebanyak-banyaknya," kata dia.
Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Lampung, Muhammad Guntur Purboyo menyebut freelance merupakan bentuk kapitalisme baru di era digital. Menurutnya, meski freelance menawarkan kebebasan waktu dan tempat, para pekerja justru tidak memiliki jaminan yang seharusnya melekat pada seorang pekerja.
Ia mencontohkan bagaimana konten kreator di platform digital hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan yang sebenarnya dihasilkan. Dalam praktiknya, pekerja freelance seringkali menanggung risiko sendiri, sementara platform hanya berperan sebagai perantara. Kondisi ini membuat mereka tanpa sadar menjadi bagian dari ‘buruh digital’ yang tereksploitasi dengan cara baru.
Guntur menilai, pilihan menjadi freelance di Indonesia tidak hanya karena sulitnya mencari pekerjaan formal, tapi juga terkait gaya hidup dan status sosial. Gen Z sering menjadikan freelancer sebagai identitas yang lebih diterima ketimbang mengaku pengangguran. Namun, di sisi lain, pola kerja ini berpotensi menimbulkan masalah solidaritas sosial karena minim interaksi langsung dan ketiadaan jaminan ketika menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, negara perlu hadir untuk memberi perlindungan bagi pekerja freelance, karena mereka tetap memberikan kontribusi pada perekonomian melalui pajak dan konsumsi. Guntur menyebut, freelance memang dapat membantu mengurangi pengangguran, tetapi tanpa regulasi yang jelas, justru memperparah ketidakpastian jaminan kerja.
"Tantangannya adalah bagaimana pemerintah meminimalisir dampak negatif dari sistem kerja ini, sekaligus memperbesar potensi positifnya bagi generasi muda dan ekonomi digital di Indonesia,"katanya.
Regulasi parsial muncul dari Pemerintah Daerah
Sejauh ini yang berupaya memberikan perlindungan kepada freelancer masih parsial di pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya, telah menganggarkan miliaran rupiah untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap ojek online (Ojol) dan freelancer yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil satu dan dua.
Adapun program ini hasil dari kerja sama Pemprov Jabar dengan BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, premi asuransi ditetapkan sebesar Rp201 ribu per tahun. Skema pembiayaannya akan dibagi bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak aplikator transportasi online.
"Kalau Rp201 ribu dibagi dua, misalnya antara Pemprov dengan kabupaten/kota, atau aplikator ojol, itu bagian dari komitmen kita untuk membangun rasa adil," kata Dedi di Gedung Sate.
Menurutnya, program ini penting karena banyak pekerja informal yang selama ini harus menanggung sendiri biaya kecelakaan kerja.
"Kalau ada kasus sopir ojol patah kaki sampai diamputasi, sekarang sudah ditanggung asuransi. Bahkan pengadaan kaki palsu pun disiapkan, termasuk pengganti penghasilan selama dirawat di rumah sakit," tegasnya.
Dedi menegaskan, Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran Rp60 miliar untuk tahap awal di sisa empat bulan tahun ini. Sementara untuk tahun depan, skema anggaran akan dihitung bersama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Namun, ia memberi catatan keras jika ada kepala daerah yang enggan bekerja sama, maka program ini tidak akan dijalankan di wilayah tersebut.
"Kalau bupati atau wali kota tidak mau kerja sama, jangan salahkan saya. Kalau rakyatnya protes, tanyakan ke kepala daerahnya," ujar Dedi.
Selain pekerja informal seperti ojol, kuli bangunan, hingga buruh pabrik kecil, Dedi juga mendorong UMKM ikut berkontribusi. Skema gotong royong pembiayaan bisa dilakukan, termasuk oleh pemilik usaha lokal yang memiliki keterbatasan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa membenarkan, perlindungan pekerja informal dan berpenghasilan rendah dijamin BPJS Ketenagakerjaannya oleh Pemprov Jabar. Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengakses melalui aplikasi Jabar SApps.
Hal tersebut termasuk freelance yang masuk dalam DTSEN desil satu dan dua. Selama terdaftar dan masuk kelompok tersebut maka akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis.
"Freelancer yang masuk kategori rentan bisa masuk/daftar, tapi kan gak semua freelancer pekerja rentan. Justru mereka kebanyakan penghasilannya banyak yang di atas rata-rata, untuk yang seperti itu, mereka didorong untuk ikut BPJS ketenagakerjaan secara mandiri," katanya.

Kelas prekariat harus berserikat
Transformasi digital yang berlangsung begitu cepat secara tidak langsung menggeser pola pikir dan kebiasaan menjadi serba instan. Salah satunya adalah dalam hal pekerjaan yang diminati Gen Z. Terdapat faktor-faktor tertentu mengapa mereka memilih menjadi freelancer.
Dosen Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, Eufrasia Kartika Hanindraputri menyampaikan bahwa alasan Gen Z tertarik dengan freelance ini karena struktur ekonomi dan nilai generasi sudah berbeda dari satu waktu ke waktu yang sekarang. Freelance merupakan salah satu bentuk gig economy, yakni sistem yang berbasis jangka pendek. Hal tersebut berarti sistem kerja freelance berdasarkan on demand dengan platform digital, tetapi Gen Z dapat melihat itu sebagai salah satu yang dapat secara instan dicapai saat ini.
“Kalau kita lihat Indonesia pasca pandemi itu sudah memperlihatkan bahwa agak berkurang nih pekerjaan tetap. Banyak lulusan yang sulit menembus pekerjaan formal karena persaingan banyak, minimnya posisi yang ditawarkan, dan banyak faktor hal lain yang membuat gen z akhirnya yang awalnya digital native, terbiasa dengan sesuatu yang fleksibel. Kreatif, ingin merdeka, tidak mau terkungkung dengan sesuatu yang bersifat konvensional, akhirnya memilih pekerjaan freelance ini sebagai salah satu pekerjaan mereka daripada mereka nganggur,” ujar Eufrasia.
Eufrasia menyebut bahwa bebas itu semu. Meskipun Gen Z merasakan fleksibilitas karena tidak terikat jam kerja dan bisa memilih proyek manapun sesuai minat mereka, tetapi mereka dituntut terus menerus untuk mencari pekerjaan baru, mengejar deadline, dan yang paling sederhana adalah tidak ada jaminan sosial.
Mengambil referensi dari seorang Associate Research Professorial sekaligus spesialis ekonomi ketenagakerjaan, Guy Standing, Eufrasia memaparkan bahwa ada yang namanya sistem prekariat. Prekariat adalah kelas baru pekerja yang gak punya jaminan kerja, gak ada perlindungan hukum, stabilitas ekonominya itu rentan. Jadi mereka bukan termasuk pekerja formal dan bukan pengusaha. Jadi mereka ada di tengah-tengah, terlihat bebas tapi tidak berdaya.
“Karena fokusnya di sosiologi pembangunan, hal-hal yang dianggap rentan ini merupakan salah satu kegagalan ekosistem. Pembangunan digital native itu tidak diikuti dengan kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi semua bentuk pekerja sehingga gen z ini menjadi salah satu korban dari sistem yang eksklusif dan ketidakadilan.”
Apabila berbicara mengenai dampak semakin maraknya Gen Z menjadi freelancer, Eufrasia berujar bahwa dampak yang terjadi tidak hanya sosial, tetapi multidimensi. Dapat diawali secara psikologis, banyal Gen Z gig worker yang burnout, kesepian, dan cemas karena ketidakpastian terus menerus. Sedangkan secara sosial, mereka akan terpisah dari dunia kerjanya seperti tidak terkoneksi dengan teman-temannya di sana sehingga tidak ada ruang kolektif di tempat kerjanya.
“Kalau dampak sosial secara luasnya akan menimbulkan risk society, atau masyarakat resiko yang tidak berasal dari sesuatu yang natural, tapi dibentuk dari sistem sosial dan sistem ekonomi itu sendiri. Risiko lebih jauhnya seperti putus kontrak, lay off, tersingkir. Kalau kamu gak bisa kerja cut off aja,” ungkap Eufrasia.
Ketidakpastian ini lah yang akan memberikan risiko secara pribadi dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup mereka akan dipertanyakan atau mungkin akan menjadi timbang dengan satu dan lainnya. Apabila dikaitkan dengan kerentanan, dampak sosialnya berupa risiko sistemik yang bersifat paradox. Ekonominya berlangsung terus tapi ada gig worker yang semakin tertinggal. Dia tidak tahu bagaimana mengikuti perkembangan ekonomi yang begitu cepat itu tadi.
Lalu hal-hal apa yang harus diperhatikan Gen Z supaya tidak menjadi korban sistem kerja yang tidak pasti? Eufrasia menyebut ada tiga hal utama. Yang pertama, Gen Z harus memahami realitas sosial di balik gig economy, yaitu sistem ekonomi global ini mendesak orang-orang yang terlibat dalam gig economy ini ke arah fleksibilitas yang tanpa proteksi. Kedua, perlunya kolektivitas antara freelancer semacam serikat pekerja di kantor. Sedangkan di tempat online bisa dengan membangun solidaritas digital, asosiasi, yang intinya adalah mengadvokasi hak-hak mereka. Ketiga, menjalin kolaborasi antar freelancer sebagai modal sosial untuk menciptakan perlindungan alternatif.
Menurut Eufrasia, ketika membutuhkan sesuatu yang berubah dari jaminan sosial itu diperlukan gerakan dari luarnya dulu, yakni diperlukan gerakan dari bottom to up. Baru dari situ, edukasi dari masyarakat bisa dilakukan dengan gerakan para freelance untuk berdialog. Sedangkan untuk pemerintah daerah bisa dibantu dengan (kehadiran) asosiasi freelancer setempat untuk memberikan bargaining position dari gig economy itu sendiri.
Lebih lanjut, Eufrasia berharap pemerintah tidak hanya membanggakan pertumbuhan dalam bentuk angka dan economy digital seperti apa, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang manusiawi dan adil, sebab inklusivitas itu penting.
“Freelancer itu bisa membentuk serikat kerja, tapi harus didukung oleh struktur pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi dengan semua kesejahteraan. Dengan begitu, gen z ini tidak menjadi pengguna teknologi ikut-ikutan freelance saja, tetapi juga sebagai agen perubahan. Jadi, pembangunan sosial dan ekonominya bisa berkelanjutan atau sustainability,” tutupnya.
Tim Penulis:
Dyar Ayu (Yogyakarta) Ni Komang Yuko Utami (Bali), Silviana Via (Lampung), Azzis Zulkhairil (Jawa Barat), Muhammad Nasir (NTB), Rangga Erfizal (Sumsel), Khusnul Hasana dan Ardiansyah Fajar (Jawa Timur)