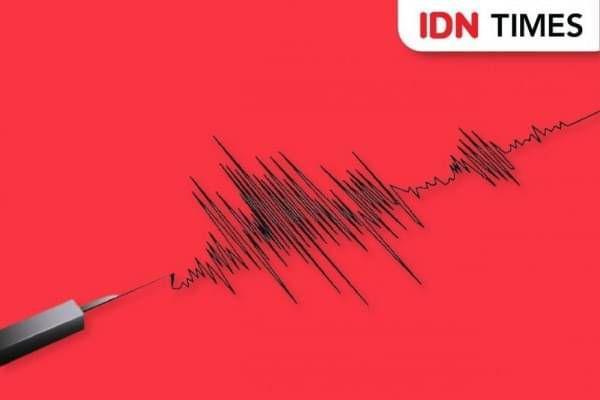[OPINI] Problem Ekologis Program Makan Siang Gratis

Program makan siang gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto bukanlah konsep baru. Program ini sebenarnya sudah pernah diterapkan di belahan dunia lain, seperti Jepang, Amerika Serikat dan Brazil. Juga pernah diterapkan di era Presiden Soeharto, meski bukan dalam bentuk makanan berat, tetapi lebih ke asupan gizi penunjang seperti susu dan makanan tambahan semacam snack.
Merujuk pada arsip foto Kompas dengan judul "Menilik Program Makan Gratis di Zaman Orde Baru," bahwa pada akhir periode Presiden Soeharto sekitar tahun 1998, program serupa pernah dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Siti Hardijanti Rukamana alias Mbak Tutut. Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk meredam efek krisis moneter saat itu.
Sementara pada program yang baru ini memang memiliki nafas serupa, tetapi berbeda konteks. Program ini muncul untuk mengatasi masalah gizi dan maraknya stunting, yang jika ditelaah juga berkaitan dengan faktor kemiskinan dan rusaknya ekosistem. Sebab stunting menurut penelitian dari Vilcons Dkk (2018) "Environmental Risk Factors Associated with Child Stunting: A Systematic Review of the Literature," sangat erat dengan rusaknya lingkungan, terutama pada air dan nutrisi pangan.
Sehingga kebijakan makan siang gratis hanya menyelesaikan permukaan, sebuah kebijakan yang hanya melihat dari hilir bukan hulu dari sebuah problem. Mengapa demikian, karena kebijakan tersebut mencoba mengatasi makanan dengan membagi makan secara gratis, tanpa melihat substansi problem, yakni kerusakan lingkungan, ketidakamanan pangan dan persoalan kemiskinan yang membatasi keluarga miskin untuk menjangkau makanan berkualitas.
Makan Siang Gratis Mengabaikan Ketahanan pangan
Konsep ketahanan pangan bersifat multidimensi, meliputi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Menurut FAO (2006) dalam sebuah brief berjudul "Food Security," ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk aktivitas aktif serta menunjang hidup sehat. Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain produktivitas pertanian, infrastruktur, kebijakan ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial ekonomi.
Terdapat tiga faktor yang signifikan terhadap ketahanan pangan, pertama soal produktivitas pertanian dan penggunaan lahan. Perlu diketahui jika lertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap sekitar 30 persen angkatan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Namun produktivitas pertanian masih menjadi tantangan besar.
Faktor-faktor seperti terbatasnya akses terhadap teknik pertanian modern, infrastruktur yang tidak memadai, dan kecilnya kepemilikan lahan menghambat kemampuan petani untuk meningkatkan hasil panen. Masalah penggunaan lahan juga penting. Dengan meningkatnya urbanisasi dan industrialisasi, lahan pertanian mengalami tekanan, berupa bayang-bayang konversi lahan.
Konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan produksi pangan dalam jangka panjang. Literatur tersebut menyoroti perlunya kebijakan dan insentif pengelolaan lahan yang lebih baik untuk melindungi dan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian.
Faktor kedua yakni, perubahan Iklim dan degradasi lingkungan. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang menimbulkan risiko signifikan terhadap ketahanan pangan. Meningkatnya suhu, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan secara langsung mempengaruhi hasil panen dan produksi pangan.
Saat ini telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi bahan pokok seperti beras, sehingga mengancam ketahanan pangan jutaan masyarakat Indonesia. Selain itu, degradasi lingkungan, termasuk penggundulan hutan dan erosi tanah, memperburuk persoalan pangan, karena secara tidak langsung mengurangi kapasitas lahan dan agroekosistem untuk mendukung pertanian.
Faktor ketiga, yakni akses ekonomi dan kemiskinan. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan, kesenjangan ekonomi masih terjadi sehingga berdampak pada ketahanan pangan. Banyak rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi. Akses ekonomi terhadap pangan merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan, dan mengatasi kemiskinan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan akses tersebut.
Kebijakan makan siang gratis mengabaikan persoalan ketahanan pangan. Program ini hampir sama dengan respons pemerintah Presiden Jokowi dalam menghadapi situasi ketahanan pangan, kala menjawab ketidakamanan pangan dengan menerapkan food estate. Sialnya, praktik food estate justru merusak kawasan gambut dan kawasan hutan. Lihat program food estate di Merauke, pemerintah memproduksi beras dengan mengalihfungsikan hutan yang didalamnya ada pohon sagu. Berusaha mengatasi pangan dengan merusak pangan lokal, sebuah logika yang sulit dinalar.
Potensi Sampah Plastik dan Food Waste
Selain tidak melihat akar persoalan, program makan siang gratis juga akan memperparah masalah lama seperti sampah plastik dan makanan. Saat ini Indonesia telah memproduksi sampah plasik yang cukup tinggi, menurut situs SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024) jumlah timbulan sampah secara nasional 37 juta ton per tahun. Jumlah timbulan sampah plastik sekitar 19.3 persen atau sekitar 6.8 juta ton, sementara sampah organik sekitar 40.9 persen atau sekitar 14.6 juta ton.
Dengan fakta demikian maka kita perlu risau, sebab program makan siang gratis yang dicanangkan diperkirakan akan menambah beban sampah yang semakin menumpuk. Jika diilustrasikan, dapat dibayangkan di satu kecamatan terdapat 12 desa yang setiap desa memiliki kira-kira memiliki minimal 2 sekolah dasar. Setiap sekolah anggap saja mempunyai sekitar 500 siswa, maka total bungkus plastik atau yang tidak bisa diurai paling tidak ada 3 jenis pembungkus yang sulit diurai, yakni plastik dan stereofoam.
Satu kali pelaksanaan program dapat memproduksi 1.500 sampah plastik. Lalu, jika ditotal dengan jumlah siswa sekitar 12.000 dari 24 sekolah dasar di satu kecamatan, maka asumsinya sehari akan menghasilkan sampah plastik sekitar 36.000 sampah plastik atau sekitar 9.600 kilogram dalam sehari. Jika ditotal keseluruhan selama 5 hari aktif sekolah maka dapat menghasilkan sekitar 180.000 sampah plastik yang setara dengan 48 ton.
Maka selama sebulan bisa mencapai 192 ton, dan setahun akan menghasilkan sampah plastik sekitar 2.304 ton. Ini hanya di satu kecamatan, belum jika nanti dikalkulasikan. Maka akan menghasilkan sampah plastik yang besar, belum lagi sampah organik sisa makanan.
Program makan siang gratis memiliki potensi signifikan dalam menambah beban ekologis ke depan. Di mana problem ini tidak melihat faktor ketahanan pangan, justru berpotensi akan semakin memperburuk ketahanan pangan, jika sumber pangan yang dipakai dari food estate dan bertumpu satu sumber pangan seperti beras saja.
Lalu, dampak yang tak kalah berbahaya dari pelaksanaan program makan siang gratis ini adalah kemungkinan pembungkus makanan akan didominasi oleh plastik dan stereofoam. Sehingga alih-alih memberikan manfaat, justru akan menambah dampak lingkungan dan memperburuk ketahanan pangan. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan lagi terkait rencana program ini, terutama dampak ekologis yang akan ditimbulkan pada kemudian hari.
Wahyu Eka Styawan
Direktur Ekseskutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur