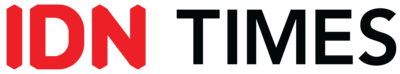Tara Basro, Antara Kesusilaan dan Pornografi
 IDN Times/Sukma Shakti
IDN Times/Sukma Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Ada inkonsistensi sikap dari Kominfo atas unggahan Tara Basro di Instagramnya. Humas Kominfo, Ferdinand Setu mengatakan foto Tara Basro berpotensi melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE tentang kesusilaan di internet, sebelum beberapa hari kemudian Menteri Johnny G Plate menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam foto sang aktris tersebut. Masalah perbedaan sikap di internal kementerian tersebut tak hanya jadi masalah miskomunikasi terhadap sebuah fenomena, namun hal tersebut juga mengindikasikan betapa kaburnya definisi pornografi.
Pernyataan Humas Kominfo bahwa unggahan Tara Basro disebut “menafsirkan ketelanjangan” sebetulnya tidak tepat. Tara Basro dalam foto tersebut memang telanjang, dengan tetap menutup bagian pribadi tubuhnya dengan tangan. Namun, yang luput dilihat oleh Kominfo adalah alasan Tara Basro tidak mengenakan baju, yakni mengkampanyekan sikap positif atas tubuh kita sendiri. Kalau yang dimaksud pornografi pada foto tersebut adalah merujuk pada eksploitasi seksual, di saat fotonya tidak merefleksikan itu sedikit pun, tentu masalah ada pada yang menafsirkan, bukan yang mengunggah.
Kekhawatiran pemerintah atas penyebaran pornografi yang kian masif memang wajar, terutama dengan keberadaan internet. Bahaya pornografi secara digital memang sangat mungkin menjangkau anak-anak. Polri mencatat, setidaknya sampai pertengahan 2019 terdapat 236 pengaduan kasus pornografi, termasuk pornografi anak. Namun, tidak berarti tingginya paparan pornografi dilawan dengan pandangan bahwa semua ketelanjangan adalah eksploitasi seksual. Ada konteks yang melekat pada sebuah materi ketelanjangan dan ada ruang yang secara spesifik ditujukan oleh penyebaran materi ketelanjangan. Melihat Negara masih memandang satu sisi pada eksploitasi seksual semata, kita patut sangsi bahwa edukasi seks akan menjadi sesuatu yang atau lazim diajarkan di ruang-ruang publik.
Pornografi atau Kesusilaan ?
Ironisnya, dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, tidak pernah benar-benar ada persepsi yang sama mengenai apa yang didefinisikan sebagai pornografi. Sebabnya adalah selalu munculnya penerjemahan secara subjektif berdasarkan nilai yang berlaku pada masyarakat saat itu.
Ditambah lagi skala subjektif seseorang atas apa yang porno dan yang tidak juga sudah pasti berbeda. Bergantung pada definisi yang ada pada aturan hukum kita pun bermasalah, karena KUHP justru menghindari penggunaan kata “pornografi” sehingga rumusan tindak pidana yang kita miliki dalam hukum pidana umum kita adalah tindak pidana kesusilaan.
Inkonsistensi rumusan nampaknya mengakar juga dari bagaimana tindak pidana kesusilaan ini diatur. Di saat kesusilaan definisinya sangat luas (contoh: menghina seseorang juga termasuk kejahatan kesusilaan), seluruh rumusan tindak pidananya (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP) justru tentang aktivitas seksual. Rumusan KUHP yang bermasalah ini yang justru membingungkan ketika ditegakkan dalam konteks kasus pornografi di internet.
Pasal 27 Ayat 1 UU ITE mengatur tentang tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Sayang tak ada penjelasan apapun mengenai apa yang dimaksud “melanggar kesusilaan”, bahkan mengkaitkannya dengan rumusan KUHP, tentang informasi yang bermuatan eksploitasi seksual pun tidak ada.
Masalah normatif pada peraturan perundang-undangan tersebut tentu menimbulkan masalah pada praktik penegakan hukumnya. Pada beberapa contoh kasus, ketidakjelasan rumusan pornografi pada Undang-Undang menjadikan penindakan kasus pornografi pun cenderung mengambang atau memaksakan unsur-unsur dari pasal-pasal terkait.
Sebagai contoh adalah, penyimpanan materi pornografi untuk konsumsi diri sendiri sebetulnya bukan merupakan tindak pidana. Dipertegas dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 6 UU Pornografi, bahwa selama untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri maka bukan termasuk perbuatan yang dilarang oleh UU ini. Pada konteks ini, seharusnya jelas bahwa yang merupakan tindak pidana adalah penyebarannya, yang dihukum pun juga sebaiknya penyebar.
Sayang pada beberapa kasus, hal ini tidak benar-benar tegas diterapkan (contoh: kasus Ariel). Tidak menindak individu yang memiliki materi pornografi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri mungkin terdengar janggal, tapi pertimbangan perlindungan kepentingan publik dalam hukum pidana berarti aktifnya hukum pidana adalah ketika materi pornografi tersebar di ruang publik. Selain itu, menegakkan hukuman pidana dengan melanggar privasi individu seperti membuka handphone atau komputer pribadi seseorang jelas pelanggaran hak asasi warga negara. Kita bisa belajar dari bagaimana negara gagal melindungi identitas dua pasien pertama positif virus corona beberapa waktu lalu.
Meninjau Ulang Sensor dan Blokir
Sekali lagi, bagaimana pemerintah sempat bereaksi untuk menutup unggahan Tara Basro yang tidak bermuatan eksploitasi seksual menunjukkan kegagapan pemerintah atas aturan hukum pornografi. Tak hanya kita masih punya legislasi yang bermasalah secara rumusan, namun senjata menutup, memblokir, menyensor dan semacamnya bisa jadi usang dan tumpul kalau tak dibarengi dengan tindakan preventif berupa edukasi menyeluruh tentang materi seksualitas yang bersifat eksploitasi dan yang bersifat edukasi.
Sensor dan blokir pornografi memang terkesan efektif, namun hanya ampuh secara sementara. Mengingat internet punya banyak saluran penyebaran untuk berbagai jenis konten. Apabila yang dikhawatirkan adalah paparan pornografi yang masif dan eksesnya terhadap bentuk-bentuk kejahatan lain (pemerkosaan atau pencabulan), maka edukasi seks akan jauh lebih efektif mengenalkan bahaya eksploitasi seksual dan menjaga diri dari kejahatan seksualitas. Begitu pula menegakkan peraturan hukum pidana secara tegas kepada penyebar pornografi akan lebih selaras dengan muatan pelanggaran kesusilaan. Sensor dan blokir yang berkelanjutan, justru akan berpotensi menjadi preseden buruk karena ditegakkan secara tegas namun buta akan konteks.
Masyarakat butuh akses informasi yang terbuka namun menegaskan batasan informasi yang baik dan buruk, benar dan salah. Secara bertahap, akses informasi yang terbuka dan upaya edukatif akan berkontribusi pada makna kesusilaan yang pasti. Sementara, menutup akses informasi justru membodohi masyarakat dan semakin mengaburkan makna kesusilaan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Kandidat Doctor of Juridical Science (SJD) Indiana University Bloomington-Maurer School of Law, Amerika Serikat.
Baca Juga: Kominfo Sebut Tara Basro Langgar UU ITE, Ini 10 Komentar Netizen